HALO NUSANTARA – Siapa yang bisa menolak pesona reuni sekolah? Suasana yang hangat, tawa yang meledak, dan wajah-wajah lama yang membawa kita berkelana ke masa paling polos dalam hidup. Bukankah terbawa perasaan ketika mendengar lagu nostalgia yang langsung menarik kita kembali ke lorong waktu, seolah semua permasalahan saat ini sirna seketika? Momen inilah yang dinanti, sebuah pelarian semu dari rutinitas.
Di balik pelukan hangat dan obrolan yang tidak ada habisnya, tersembunyi sebuah dinamika yang jarang diakui, namun faktual. Atmosfer nostalgia yang begitu pekat menciptakan ruang aman untuk kemesraan yang instan dan berisiko tinggi. Dan, tanpa sadar membuka pintu hati lebar-lebar, mengizinkan kilas balik mengambil alih nalar dan akal sehat.
Namun, apa yang sering dianggap sebagai “cinta lama yang bersemi kembali” hanyalah sebuah pseudo-asmara, fantasi romantis yang dibangun dari ilusi masa lalu. Nostalgia berubah menjadi aphrodisiac yang menghasilkan euforia dan mengaburkan penilaian dari komitmen nyata yang telah dibangun. Inilah bahaya yang mengintai di balik senyum dan kenangan indah reuni sekolah.
Mengurai “Pseudo-Asmara”
Lalu, apa sebenarnya “pseudo-asmara”? Ia bukanlah cinta dan kasih sayang yang otentik, melainkan stimulasi perasaan semu yang dirakit dari serpihan kenangan dan situasi. Bayangkan sebuah resep yang terdiri dari segenggam nostalgia, sesendok penasaran akan “what if“, dan dibalut pujian yang mengembalikan ego di waktu reuni sekolah. Apakah ini asmara, atau hanya respons alamiah terhadap lingkungan yang dirancang untuk membuat kita merasa muda kembali?
Ikatan yang terbentuk akan terasa sangat nyata dan mendalam, namun pada dasarnya sangat rapuh. Filsuf Prancis, Jean-Paul Sartre (No Exit, 1944), pernah berkata, “Hell is other people“. Pada konteks ini, siksaan sesungguhnya mungkin datang dari bayangan diri sendiri di masa lalu, yang memproyeksikan kebutuhan akan validasi kepada orang lain. Relasi semacam ini merupakan sebuah ilusi yang justru menjauhkan dari realitas komitmen yang sebenarnya.
Pseudo-asmara ibarat lampu disco di sebuah pesta. Dalam kegelapan, dengan iringan musik yang menggoda, setiap kilauannya terlihat memesona dan penuh janji. Kita menari di bawah sinarnya, terbuai oleh pesona semu yang berkedip. Namun, pernahkah bertanya, “Apa yang tersisa ketika lampu utama menyala dan pesta usai?”
Ketia matahari terbit, yang tertinggal hanyalah ruangan hampa dan kesadaran akan kenyataan. Kilaunya yang magis seketika lenyap, digantikan oleh cahaya terang yang memperlihatkan segala sesuatu apa adanya. Demikian pula dengan pseudo-asmara; hanya hidup dalam fatamorgana waktu reuni sekolah, dan mati ketika kembali menghadapi rutinitas maupun konsekuensi di kehidupan nyata.
Elemen Pseudo-Asmara
Nostalgia bukan hanya kerinduan biasa, namun aphrodisiac paling ampuh yang memutar balik logika. Perasaan semu tersebut secara efektif menapis semua kenangan buruk, dan hanya menyisakan memori indah yang disepuh zaman. Bagaimana mungkin akan dapat berpikir jernih ketika kesadaran disergap badai “neurokimia” kebahagiaan masa lalu? Psikolog Clay Routledge (The Handbook of Nostalgia, 2016), menyebut nostalgia sebagai “campuran antara memori dan kerinduan yang dilekatkan pada makna emosional“. Pada dalam konteks reuni sekolah, makna emosional akan mudah sekali disalahartikan sebagai ketertarikan.
Di ajang reuni sekolah, bukan lagi bertemu dengan sosok manusia seutuhnya, melainkan dengan proyeksi diri masa lalu yang terdistorsi. Kita akan melihat fatamorgana “si tampan” yang sekarang sukses, bukan suami yang sedang berjuang untuk keluarganya. Ilmuwan kognitif Donald Hoffman (The Case Against Reality, 2019), secara tegas menyatakan, “We are not seeing reality as it is“. Bukankah yang dikejar sebenarnya adalah hantu dari versi diri kita yang lebih muda?
Pada kehidupan saat ini yang penuh tuntutan, pujian seperti “Kamu tidak berubah” atau “Sekarang semakin menarik” menjadi obat penenang bagi ego yang lapar santapan hati. Perhatian yang intens selama waktu reuni sekolah, terasa lebih memuaskan daripada apresiasi pasangan sah yang istiqomah dalam menjaga komitmen. Filsuf Søren Kierkegaard (1843) mengatakan: “Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards“. Namun, apakah kita justru terjebak mencari validasi dengan memutar waktu ke belakang?
Suasana reuni sekolah yang dirancang seperti laboratorium emosional, di mana memori melankolis dapat menciptakan ilusi kemesraan. Pada kondisi lingkungan seperti itu, batas sosial dengan mudahnya akan menjadi luruh. Fisikawan Albert Einstein (The Saturday Evening Post, 1929), secara jenial pernah berkata: “Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one“. Lantas, ilusi mana yang lebih dipilih: “Fantasi semalam yang menggoda ataukah realitas komitmen yang telah lama dijaga?”
Mengapa Pseudo-Asmara Berbahaya?
Bahaya terbesar pseudo-asmara terletak pada sifatnya yang halus dan tidak terasa seperti ancaman. Ia tidak datang sebagai badai, melainkan meresap seperti kabut yang secara perlahan mengaburkan batas moralitas dan etika. Bagaimana mungkin akan waspada terhadap sesuatu yang terasa begitu natural dan menyenangkan? Seperti kata filsuf Cina, Lao Tzu (Tao Te Ching, abad ke-6 SM), “The journey of a thousand miles begins with a single step“. Langkah awal menuju perselingkuhan, seringkali dimulai dari obrolan ringan yang dianggap biasa dan tidak berdosa.
Perselingkuhan emosional yang halus merupakan bentuk pengkhianatan tanpa sentuhan fisik, namun lukanya sama dalamnya. Biasanya dimulai dari berbagi cerita hati, keluhan rumah tangga, dan impian yang seharusnya menjadi milik pasangan. Bukankah ini bentuk ketidaksetiaan yang penuh tipu muslihat, ketika hati sudah berpaling sebelum raga bergerak? Psikolog Shirley Glass dalam bukunya, “Not Just Friends” (2003), memperingatkan bahwa dinding pelindung hubungan secara perlahan akan runtuh, ketika mulai berbagi emosi mesra dengan orang lain.
“Kami cuma berteman lama,” biasanya selalu menjadi “mantra” pembenar yang paling sering diucapkan untuk penyangkalan (denial). Dengan membohongi diri sendiri dan percaya bahwa yang terjadi hanyalah “persahabatan” yang tulus. Namun, bisakah jujur: “Apakah obrolan dengan teman biasa membuat jantung berdebar dan wajah tersipu?” Sigmund Freud (Letters, 1896), bapak psikoanalisis, dengan tegas menyatakan, “Unexpressed emotions will never die. They are buried alive and will come forth later in uglier ways“. Emosi yang ditutupi, akan bermetastasis menjadi krisis yang lebih besar.
Setiap detik yang dihabiskan untuk membangun pseudo-asmara adalah waktu yang dicuri dari relasi nyata. Energi emosional yang terbatas kini terbagi, dan pasangan yang sah hanya akan mendapat residunya. Tidakkah ironis ketika lebih bersemangat membalas chat mantan kekasih daripada menanyakan keadaan pasangannya sendiri? Seperti peringatan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits, “Sungguh, amal itu tergantung niatnya” (HR. Bukhari-Muslim). Jika niat hati sudah berpihak, maka bukankah itu sudah merupakan pengkhianatan terhadap ikrar suci pernikahan?
Antara Diri, Pasangan, dan Tanggung Jawab
Permasalahannya bukan terletak pada nostalgia itu sendiri, melainkan ketiadaan kendali diri dalam menikmatinya. Kenangan indah merupakan warisan dari masa lalu yang berharga, tetapi diri sendirilah yang memutuskan apakah akan menjadikannya sebagai permata atau petaka. Bukankah kedewasaan sesungguhnya terletak pada kemampuan membedakan antara melangkah ke masa lalu untuk mengenang versus terjebak di dalamnya? Seperti kata filsuf Stoic Epictetus (Enchiridion, abad ke-2), “We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them“. Nostalgia merupakan keadaan eksternal; sedangkan tanggapan yang menentukan akibatnya.
Sebelum terhanyut dalam pseudo-asmara, maka perlu melakukan refleksi yang jujur terhadap diri sendiri: Apakah yang sebenarnya kucari? Apakah ini pelarian dari masalah yang kuhadapi di relasi nyata? Psikolog Carl Jung (Psychology and Alchemy, 1944) mengingatkan, “Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes“. Kesadaran dari ilusi pseudo-asmara terjadi ketika berani menyelami motivasi terdalam diri sendiri, bukan dengan mencari pelampiasan di luar rumah.
Komitmen bukanlah perasaan pasif yang hanya mengandalkan kebahagiaan sesaat, melainkan pilihan aktif yang diambil berulang kali setiap hari. Memilih untuk tidak membalas pesan yang menggoda, atau memilih untuk tidak berduaan, merupakan bentuk konkret dari kesetiaan. Seperti dinyatakan filsuf eksistensialis Jean-Paul Sartre (Being and Nothingness, 1943), “Man is condemned to be free“. Dalam kebebasan, bukankah kita justru terperangkap untuk memilih antara fantasi semu yang menghancurkan ataukah realitas komitmen yang membangun?
Nostalgia yang Sehat
Reuni sekolah seharusnya menjadi titik balik untuk memperkuat ikatan persaudaraan, bukan meruntuhkan bangunan komitmen yang telah susah payah dijaga. Pseudo-asmara mungkin terasa manis di mulut, namun meninggalkan kesan pahit yang berkepanjangan dan luka mendalam. Bukankah lebih baik belajar dari masa lalu, tanpa perlu mengulangi kesalahan yang sama?
Hadirilah reuni dengan niat untuk bersilaturahmi, bukan dengan agenda asmara terselubung untuk membangkitkan romansa masa lalu. Seorang penyair dan sufi ternama, Jalaluddin Rumi (Masnavi, abad ke-13), berpesan bijak, “Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder“. Marilah kita hujani reuni dengan kata-kata yang menumbuhkan persahabatan, bukan dengan rayuan kasih semu yang destruktif. Bawalah pulang kenangan indahnya, dan tinggalkan pseudo-asmara yang toksik.
Allah SWT telah mengingatkan dalam Al-Qur’an, “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’ : 32). Ayat tersebut bukan hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala jalan yang mendekatinya, termasuk pseudo-asmara yang berbahaya. Biarkan masa lalu tetap menjadi memori, jauhkan dari niat yang mengotori hati dan merusak kehidupan nyata. Pilihlah yang halal, tinggalkan yang haram dan semu, kembalilah ke pasanganmu yang setia menunggu dan menjagamu.
Penulis: Harry Yulianto – Akademisi STIE YPUP Makassar
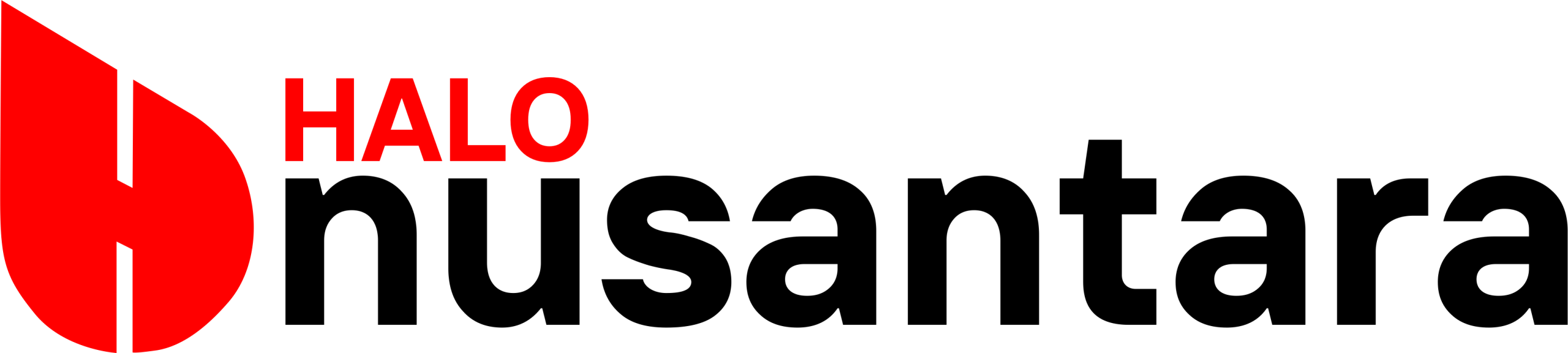







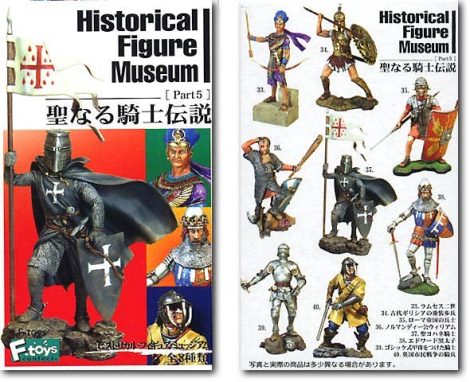






Komentar