HALO NUSANTARA – Dalam birokrasi kontemporer, fenomena waktu kerja yang tersita untuk urusan asmara terlarang bukanlah hal langka. Waktu yang menjadi hak masyarakat justru tergerus oleh interaksi digital yang privat. Kondisi ini telah menjadi pola berulang yang memperoleh amplifikasi media, menandai distorsi terhadap akuntabilitas layanan publik.
Sering kali muncul pembelaan bahwa perselingkuhan adalah ranah privat yang tidak pantas diintervensi. Argumen sempit ini memisahkan moralitas personal dan tanggung jawab profesional, sehingga pelanggaran etika serius sering diselesaikan di belakang pintu tertutup.
Anggapan tersebut keliru secara fundamental. Sebab, dalam perspektif hukum dan etika pemerintahan, perselingkuhan yang dilakukan abdi negara bukan hanya pelanggaran privat, melainkan titik nadir integritas yang menandai keruntuhan moral. Lebih dari itu, perbuatan ini dapat menjadi pintu masuk bagi dampak sistemik yang mengikis disiplin dan tata kelola pemerintahan. Landasan hukumnya jelas: Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS secara tegas menempatkan perbuatan tercela sebagai pelanggaran, yang bersumber dari krisis integritas tersebut.
Tulisan ini akan menguraikan transformasi persoalan privat menjadi krisis publik yang menggerus fondasi penyelenggaraan negara. Sebagai sebuah opini yang merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili institusi pemerintah mana pun, tulisan ini disampaikan dengan itikad baik dan niat konstruktif-solutif untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas birokrasi, serta pencegahan korupsi.
Selingkuh sebagai Cermin Rapuhnya Integritas dan Karakter
Setiap pegawai pemerintah dibiayai uang rakyat dan diberikan amanah mengelola kepentingan publik. Integritas bukanlah atribut tambahan, melainkan modal dasar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan bahwa integritas adalah nilai yang utuh, terbentuk dari keselarasan antara kehidupan pribadi dan publik. Ketika seorang abdi negara berselingkuh, ia tidak hanya melanggar komitmen pribadi, tetapi juga menunjukkan kerapuhan karakter yang menjadi fondasi tugasnya. Logikanya sederhana: kepercayaan publik dibangun di atas konsistensi karakter. Seseorang yang tidak jujur dalam komitmen privatnya, telah menggugurkan prasyarat moral untuk memegang amanah publik.
Integritas dalam menjaga komitmen personal merupakan indikator krusial kelayakan memegang amanah publik. Filsuf Socrates (469-399 SM) menegaskan prinsip sophrosyne (penguasaan diri) sebagai landasan etis seorang pemimpin. Seorang aparatur negara harus mampu menguasai dirinya sendiri sebelum mengurusi hajat hidup orang banyak. Ketidaksetiaan menunjukkan kegagalan fundamental dalam pengendalian diri.
Perilaku selingkuh bertentangan dengan nilai-nilai inti dalam regulasi. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menegaskan nilai dasar seperti akuntabilitas, keteladanan, dan kepatuhan hukum. Seorang pelaku perselingkuhan telah gagal pada ketiganya. Karena integritas bersifat utuh dan tidak terbagi, kegagalan menegakkannya dalam kehidupan pribadi, otomatis meruntuhkan klaim atas integritas profesional di dunia publik.
Di balik kerapuhan integritas, penting menelaah akar pemicunya. Lingkungan birokrasi yang sarat tekanan deadline, overwork, dan dinamika politik internal dapat memicu burnout serta stres kronis. Pada kondisi kelelahan emosional dan mental yang berkepanjangan, individu menjadi rentan mencari pelarian di luar hubungan yang sah. Perselingkuhan dalam konteks ini, meski tidak dapat dibenarkan, sering kali bukan semata niat jahat, melainkan gejala kegagalan sistem melindungi kesehatan mental aparatur.
World Health Organization (2022) mengklasifikasikan burnout sebagai fenomena okupasional, mengukuhkan bahwa beban kerja dan lingkungan tidak sehat berkontribusi terhadap penurunan ketahanan psikologis. Selain kegagalan moral personal, perselingkuhan juga cerminan masalah struktural yang membutuhkan pendekatan preventif holistik.
Prinsip “Netralitas dan Tidak Mendiskriminasi” dalam Kode Etik PNS dapat terganggu ketika aparatur negara terlibat konflik kepentingan akibat hubungan asmara. Gangguan tersebut bukan hanya konsep teoretis, melainkan dapat berakibat terhadap pelanggaran dalam praktik. Laporan Tahunan Ombudsman (2022) menunjukkan 17% pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diskriminatif dan tidak adil, indikasi kuat bahwa konflik kepentingan personal dapat meluas ke ruang publik.
Di sisi lain, batas privasi seorang abdi negara patut dihormati. Namun, pembeda krusialnya adalah ketika perilaku privat seperti perselingkuhan terbukti mempengaruhi kinerja, menciptakan konflik kepentingan, atau merusak citra dan keyakinan publik. Pada kondisi ini, tindakan tersebut telah melampaui batas ‘urusan privat’ dan masuk ranah ‘kepentingan publik’.
Dampak Sistemik terhadap Kinerja dan Layanan Publik
Perselingkuhan menuntut investasi waktu, energi emosional, serta fokus mental yang besar, di mana aset yang berharga seharusnya dicurahkan untuk melayani publik. Konflik batin dan upaya menyembunyikan rahasia dapat mengakibatkan mental absence atau presenteeism, fenomena di mana pekerja hadir fisik tetapi fungsi kognitif dan produktivitasnya menurun (WHO, ICD-11, 2022).
Tren kerja hybrid dan remote pasca-pandemi mengaburkan batas antara kehidupan personal dan profesional. Godaan untuk melakukan digital infidelity semakin tinggi. Waktu kerja fleksibel dan akses konstan ke perangkat digital akan menciptakan gap terhadap interaksi yang tidak semestinya selama jam kerja. Fasilitas teknologi yang seharusnya mendukung efisiensi, justru berpotensi disalahgunakan untuk hubungan terlarang. Kondisi ini memperburuk mental absence, menciptakan penyalahgunaan waktu, serta sumber daya negara yang sulit terdeteksi pengawasan konvensional.
Kondisi presenteeism jelas bertentangan dengan kewajiban melaksanakan tugas secara cermat dan penuh tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam PP 94/2021. Akibatnya, bukan hanya kinerja individu yang menurun, melainkan masyarakat dan rekan kerja yang turut dirugikan.
Kajian global Gallup (2022) mengungkapkan pekerja yang mengalami burnout menunjukkan produktivitas 37% lebih rendah dan tingkat presenteeism yang signifikan. Dalam keadaan mental demikian, muncul kecenderungan menyalahgunakan fasilitas negara.
Bentuknya beragam, dari penggunaan kendaraan dinas hingga manipulasi anggaran. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2022 menunjukkan ketidakpatutan perjalanan dinas senilai Rp 287 miliar, dengan modus fiktif sebagai penyumbang terbesar. Data ini mengonfirmasi bahwa kepentingan personal terselubung berujung pada manipulasi anggaran publik, yang telah bergeser menjadi tindakan koruptif.
Ketika perselingkuhan terjadi di lingkungan kerja, dampaknya meracuni budaya organisasi. Hubungan tidak profesional menciptakan office politics yang tidak sehat, di mana kolaborasi digantikan kecemburuan dan intrik. Dinamika tim yang kohesif, vital bagi efektivitas birokrasi, akan runtuh.
Peter Drucker dalam Management: Tasks, Responsibilities, Practices (1973) menegaskan bahwa budaya perusahaan menentukan apa yang dianggap sebagai hasil atau prestasi. Budaya kerja yang teracuni perselingkuhan akan menghancurkan rencana strategis dan prosedur kerja baku.
Lingkungan penuh prasangka dan ketidakadilan akan mengalienasi pegawai berintegritas dan memicu brain drain. Birokrasi kehilangan aset terpenting, yakni: sumber daya manusia berkualitas dan bermental sehat. Lebih dari itu, perselingkuhan mengikis aset non-materiil paling berharga: kepercayaan publik.
Pintu Masuk Menuju Penyalahgunaan Jabatan dan Korupsi
Perselingkuhan dalam birokrasi dapat berevolusi menjadi pemantik penyalahgunaan jabatan dan korupsi. Perselingkuhan bukan aktivitas bebas biaya; sering kali membutuhkan dana besar untuk hadiah mewah, akomodasi, hingga liburan. Ketika gaji pokok tidak mencukupi, godaan mencari pendapatan ilegal muncul. Pada beberapa kasus korupsi yang diungkap KPK, motif perselingkuhan sering menjadi pendorong.
Laporan Penelitian Modus dan Pola Gratifikasi KPK (2021) mengidentifikasi pemberian hadiah atau fasilitas kepada pihak ketiga, termasuk pasangan selingkuh, sebagai modus gratifikasi yang marak. Hubungan tidak etis dapat bertransformasi menjadi saluran menyalahgunakan wewenang, yang dilarang oleh UU Tipikor.
Pada titik ini, selingkuh bertransformasi dari urusan hati menjadi ‘economic motivator‘ yang berbahaya. Dorongan memuaskan kebutuhan dapat mendorong aparatur negara menggelapkan uang negara, memanipulasi anggaran, atau menerima suap. Bahaya terbesar sering kali bukan dari niat jahat terencana, melainkan dari sikap tidak bertanggung jawab pegawai yang terjerat dalam siklus pembiayaan perselingkuhan.
Pada kondisi ini, peringatan Edmund Burke dalam Reflections on the Revolution in France (1790) menjadi sangat relevan: ‘yang diperlukan untuk kemenangan kejahatan adalah orang-orang baik tidak melakukan apa-apa.’ Membiarkan pelanggaran moral sistematis tanpa konsekuensi sama dengan membiarkan kanker ketidakjujuran menggerogoti birokrasi.
Jabatan dapat disalahgunakan untuk menguntungkan pihak ketiga. Wewenang dalam pengadaan barang/jasa dapat dimanipulasi agar perusahaan milik selingkuhan memenangkan tender. Dalam rekrutmen, posisi strategis bisa diisi berdasarkan kedekatan asmara, bukan kompetensi. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 63 melarang nepotisme, yang dalam praktiknya mencakup hubungan perselingkuhan.
Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk nyata konflik kepentingan yang merusak. Ketika keputusan didasarkan pada kepentingan pribadi, kepentingan negara dan masyarakat tersingkirkan.
Data Statistik Penindakan KPK Triwulan IV 2023 menyebutkan 22% kasus suap melibatkan pertukaran janji dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan kedekatan personal, sering mencakup hubungan asmara terselubung. Temuan empiris ini membuktikan konflik kepentingan akibat perselingkuhan melemahkan tata kelola pemerintahan dan merugikan keuangan negara.
Meruntuhkan Fondasi Kepercayaan Publik
Dampak perselingkuhan yang dilakukan abdi negara di era digital cenderung lebih masif dan instan akibat amplifikasi media sosial. Skandal tidak hanya menyebar cepat melalui Instagram atau TikTok, tetapi juga memicu krisis trust generasi muda terhadap institusi pemerintah.
Kecenderungan ini selaras dengan temuan Edelman Trust Barometer (2023) di Indonesia, di mana 62% responden menempatkan ‘kemampuan memimpin yang etis’ sebagai kualitas terpenting seorang pemimpin pemerintahan, mengalahkan kompetensi dan inovasi. Integritas moral menjadi pertimbangan utama publik dalam menilai kinerja pemerintah.
Bagi masyarakat, seorang abdi negara adalah personifikasi dari negara itu sendiri. Setiap interaksi membentuk persepsi publik tentang apakah pemerintah dapat dipercaya. Ketika skandal moral melekat pada seorang abdi negara, dampaknya menyebar layaknya efek domino. Citra buruk individu dengan cepat digeneralisasikan menjadi citra buruk instansi bahkan institusi pemerintah secara keseluruhan.
Kerusakan kredibilitas bersifat sistemik dan strategis. John Locke (1689) menegaskan legitimasi pemerintah berakar pada persetujuan dan trust yang diberikan rakyat. Setiap skandal moral secara perlahan merusak fondasi kepercayaan, menciptakan krisis legitimasi yang melemahkan stabilitas sosial.
Kontradiksi antara apa yang ‘dikatakan’ dan ‘dilakukan’ menciptakan jurang hipokrisi mendalam. Bagaimana mungkin masyarakat mempercayai abdi negara yang menjadi duta program ketahanan keluarga, sementara kehidupan rumah tangganya hancur?
Kepercayaan publik adalah social capital yang paling berharga dan mudah rapuh. Seperti dikemukakan Francis Fukuyama dalam bukunya Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity (1995), tesis utamanya menyatakan bahwa ‘Kemakmuran suatu bangsa sangat bergantung pada tingkat kepercayaan sosialnya.’ Kepercayaan yang runtuh akibat skandal moral berulang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dibangun kembali, dengan biaya sosial dan politik yang besar.
Bukti empiris memperlihatkan setiap kasus perselingkuhan yang dibiarkan mengikis social capital (Putnam, 2000) dan merusak public trust (OECD, 2017). Menurut Rothstein dalam The Quality of Government (2011), ketika kepercayaan publik terkikis, konsekuensinya ditanggung masyarakat melalui birokrasi tidak efisien, kebijakan diragukan, serta penurunan kualitas layanan publik.
Menjaga Marwah Birokrasi
Upaya menjaga marwah birokrasi harus dimulai dari koreksi fundamental, yakni: menanggalkan pandangan keliru tentang perselingkuhan. Perselingkuhan yang dilakukan abdi negara merupakan gejala runtuhnya integritas yang dampaknya sistemik dan berujung terhadap pelanggaran disiplin multidimensi. Dari rapuhnya integritas, inefisiensi, penyalahgunaan sumber daya, hingga potensi korupsi, semua bermuara pada erosi kepercayaan publik.
Menyadari kompleksitas dampak tersebut, negara tidak boleh lagi bersembunyi di balik dalih “urusan privat”. Membiarkan pelanggaran moral sistematis tanpa konsekuensi, sama dengan membiarkan kanker ketiadaan integritas menggerogoti birokrasi dari dalam.
Kualitas institusi pemerintahan ditentukan oleh kualitas setiap individu di dalamnya. Lee Kuan Yew (2000) menegaskan pemerintahan yang baik bergantung pada kualitas orang-orangnya. Integritas dan kompetensi birokrat menjadi tulang punggung negara.
Di sisi lain, setiap tuduhan perselingkuhan harus melalui proses hukum yang fair. Prinsip presumption of innocence harus dijunjung tinggi. UU ASN menjamin hak untuk membela diri dan mendapatkan proses hukum yang adil.
Sebagai perbandingan, Singapura menerapkan zero tolerance terhadap perilaku tidak etis, termasuk perselingkuhan. Integritas moral sebagai prasyarat mutlak untuk memegang jabatan publik. Kebijakan tegas ini menjadi fondasi clean and effective government (World Bank, 2020).
Sebagai implementasi, mekanisme pengawasan proaktif mutlak diperlukan. Setiap instansi dapat mengadopsi sistem Whistleblowing System (WBS) terintegrasi yang memungkinkan pelaporan anonim dan terlindungi. Panduan efektif WBS untuk sektor publik telah dirumuskan KPK (2022).
Langkah konkret yang diperlukan sebagai berikut. Pertama, pembinaan mental dan karakter: Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu mengintegrasikan Modul Penguatan Ketahanan Keluarga dan Etika Kepemimpinan Publik dalam setiap diklat, khususnya untuk jabatan strategis. Implementasinya harus operasional, melalui coaching berkala dan konseling individu yang mudah diakses dan terjamin kerahasiaannya.
Kedua, penegakan hukum substantif: Pasal 3 PP 94/2021 tentang “perbuatan tercela” harus ditafsirkan mencakup perselingkuhan yang terbukti merusak citra instansi, dengan sanksi proporsional hingga pemecatan.
Ketiga, pendeteksian dini konflik kepentingan: membangun sistem terintegrasi dengan sistem kepegawaian yang dapat mendeteksi potensi konflik dan memberikan alert otomatis.
Keempat, pemanfaatan teknologi: audit trail dalam sistem TI dapat memantau pola penggunaan tidak wajar. Analisis data perjalanan dinas, pengadaan, dan anggaran dapat mengungkap red flag penyimpangan.
Maka, saatnya beralih dari wacana menjadi aksi. Bagi abdi negara, buktikan integritas sebagai sikap hidup, dimulai dari kesetiaan dalam keluarga. Bagi masyarakat, jadilah pengawas yang cerdas dan pro-aktif. Laporkan indikasi penyimpangan melalui saluran sah dengan bijak dan bukti jelas.
Birokrasi yang bersih lahir dari konsistensi dan komitmen terhadap integritas, bukan sekadar wacana. Tanggung jawab ini bersifat moral dan sosial. Oleh karena itu, kredibilitas birokrasi Indonesia hanya akan tumbuh dengan penegakan hukum yang tanpa tebang pilih, serta pembinaan karakter yang berkelanjutan, termasuk dalam menjaga kesetiaan sebagai cerminan integritas dasar. Pada akhirnya, menjaga integritas bukanlah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan komitmen total maka titik nadir integritas yang ditandai oleh penyimpangan moral seperti perselingkuhan dapat ditinggalkan, dan fondasi birokrasi yang dipercaya dapat dibangun kembali.
Penulis: Harry Yulianto – Akademisi STIE YPUP Makassar
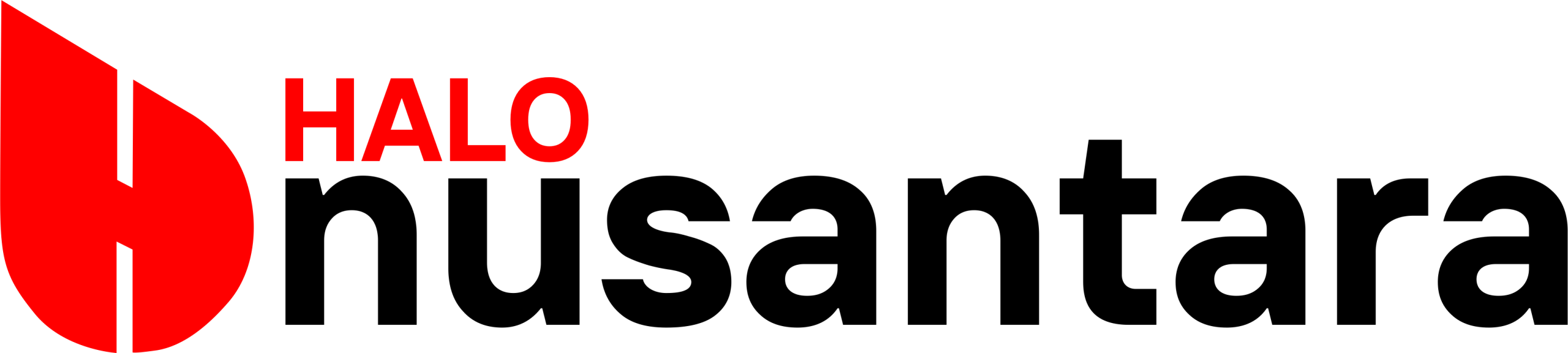







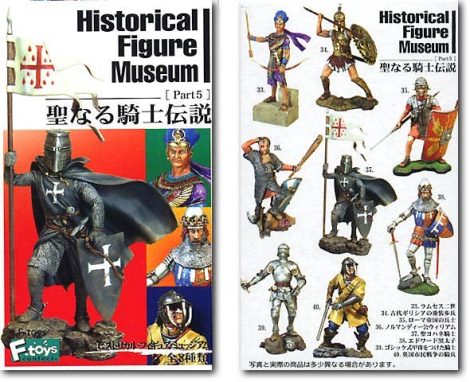






Komentar